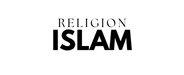– Siapakah Abudiddin al-Iji dan mengapa dikatakan bahwa di awal kitabnya, *Mawaqif*, terdapat pujian yang berlebihan? Kepada siapa pujian itu ditujukan dan mengapa hal itu dikritik?
Saudara kami yang terhormat,
Adududdin al-Iji,
Dia adalah seorang ahli kalam, ushul, dan bahasa.
“Mendirikan wakaf”
Karya yang berjudul … juga berkaitan dengan ilmu kalam.
Karya ini ditulis pada masa pemerintahan dinasti Inju, di mana penulisnya menjabat sebagai qāḍīl-qudāt (hakim agung).
Pangeran Shiraz, Jamaluddin Abu Ishaq
Setelah pendahuluan singkat yang menyatakan kepada siapa buku ini didedikasikan, buku ini terdiri dari enam bagian.
Topik yang dibahas dalam pertanyaan mungkin berkaitan dengan dedikasi singkat ini.
Setiap penulis, di awal karyanya, memberikan informasi singkat tentang karya tersebut, dan mereka yang berkontribusi dalam penulisan dan persiapan karya tersebut disebutkan dan, dalam arti tertentu, diberi ucapan terima kasih.
Nah,
Di dalam
Ia mendedikasikan karyanya kepada Emir Shiraz, Abu Ishaq, yang menjadi penyebab penulisan karya penting seperti de Mevakıf, dan juga menyebutkan beberapa karakteristik terkenal darinya.
Setelah informasi singkat ini
el-İci
kehidupan, metode, dan pandangan tentang teologi.
“Mendirikan wakaf”
Mari kita coba menjawab pertanyaan tentang karya berjudul tersebut dan karya-karyanya yang lain:
Jawaban 1: Adud al-Din al-Iji
Abu al-Fadl Adud al-Din Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Abd al-Gaffar al-Iji (meninggal 756/1355) adalah seorang ulama kalam, usul, dan bahasa, serta dikenal sebagai seorang muhaddiq (peneliti).
Ia lahir di Îc, dekat Shiraz, pada tahun 680 (1281). Ia berasal dari keluarga kaya yang dikatakan sebagai keturunan Abu Bakar, dan ayahnya adalah hakim di kota kelahirannya.
Setelah dibesarkan di Îc, Adudüddin pergi ke Shiraz, lalu ke Sultaniye, ibu kota baru yang didirikan oleh Ilkhanat, dan berada di bawah perlindungan Perdana Menteri Ilkhanat, Rashid al-Din Fazlullah. Pada saat yang sama, Ibnu’l-Fuwati, yang juga mengunjungi kota yang sama, mengatakan bahwa Îcî datang ke Sultaniye pada tahun 706 (1306) dan menjadi murid Reşîd al-Din dalam ilmu, hikmat, dan sastra. Ia juga menyatakan bahwa selama berada di sisi Reşîd al-Din, Îcî condong ke filsafat, mengadopsi beberapa pandangan yang salah dalam bidang akidah, dan mengembangkan kebiasaan buruk, sehingga hubungannya dengan ayahnya memburuk. Namun, kemungkinan Ibnu’l-Fuwati, yang datang ke Sultaniye untuk mendapatkan posisi di istana Ilkhanat, mengajukan klaim-klaim ini untuk menuduh Îcî yang menghalangi ambisinya.
(van Ess, WO, IX [1977-78], hlm. 272)
Olcaytu Khan
Îcî, yang menjabat sebagai hakim di Sultâniye pada masa itu (1304-1316), berada di sebelah kanan pondok.
di madrasah keliling yang ikut serta dalam ekspedisi
Ia menjadi pendidik. Setelah kematiannya, putranya Abu Said Bahadur Khan yang menggantikannya, menjabat sebagai hakim agung di Sultaniye. Setelah kematian Rashidu’d-Din, atas permintaan putranya Ghiyath al-Din Muhammad yang menjadi menteri, ia kembali ke Shiraz pada tahun 727 (1327) dan mulai menjabat sebagai hakim di sana.
“Al-Fawaid al-Giyasiyah wa Syarhu al-Mukhtasar”
Tidak diketahui sampai kapan Îcî, yang mendedikasikan karyanya kepada Gıyâseddin, memegang jabatan ini di Şîraz.
Sumber-sumber menyebutkan bahwa ia meninggalkan Shiraz setelah beberapa waktu dan kemungkinan menghabiskan sebagian hidupnya di Shebunker. Setelah kematian Abu Said pada tahun 736 (1335-1336) dan eksekusi Ghiyath al-Din, yang menandai berakhirnya kekuasaan Ilkhanid, Ijî kembali ke Shiraz di bawah pemerintahan Amir Abu Ishaq, yang merupakan anggota keluarga Incu, penguasa baru di sana.
kādılkudât
dan
Hafiz Syirazi
juga bertemu dengannya. Hâfız menyebutnya sebagai salah satu dari lima tokoh penting yang berperan dalam pembangunan wilayah Persia dan
“Sultan dari segala sultan di negeri pengetahuan”
sebagai.
(Kumpulan Puisi Hafiz, hlm. 537)
Îcî
Meskipun secara aktif berpartisipasi dalam upaya mediasi, ia tidak dapat terhindar dari pengepungan Mubāriz al-Dīn Muḥammad ibn Muzaffar, pendiri dinasti Muzaffarī, dan secara diam-diam meninggalkan Shiraz (754/1353) untuk kembali ke kampung halamannya. Di sana, Îjī, yang dilindungi oleh Shah Shujā’, ditangkap oleh gubernur Kirman setahun kemudian karena alasan yang tidak diketahui dan dipenjara di Direymiyān, di mana ia meninggal.
Adududdin al-Iji
Di antara guru-guru Îjī terdapat Çârperdî, murid Kādī Beyzâvî, dan Kutbüddîn-i Şîrâzî, murid Nasîrüddîn-i Tûsî. Antara Îjī dan Çârperdî muncul beberapa perbedaan pendapat, dan perdebatan mereka terkenal di kalangan cendekiawan. Di antara murid-murid Îjī yang menulis syarah atas kitabnya, al-Mawāqif dan Fawaid, adalah Shams al-Din al-Kirmānī, yang juga menulis catatan pinggir untuk Syarh al-Mukhtasar dan dianggap sebagai murid terpenting Îjī.
Sa’deddin at-Taftazani
, yang menulis syarah untuk al-Mawāqif dan Jawāhir al-Kalām, serta catatan kaki untuk Syarh al-Mukhtasar
Sayyid Syarif al-Jurjani
dan nama-nama seperti Abu Muhammad Abdullah b. Sa’d al-Afifi al-Kazwini, yang dikenal sebagai Ibnu Qadi al-Qirim, dapat disebutkan.
Jawaban 2: Metodenya
Îcî,
Ia memilih metodologi tiga bidang yang berbeda sebagai subjek pemikirannya: Usûlü’d-dîn, usûl-i fıkıh, dan usûlü’l-luga. Dalam bidang pertama, ia meneliti aqidah, dalam bidang kedua, ia meneliti prinsip-prinsip fiqh, dan dalam bidang ketiga, ia meneliti dasar-dasar ilmu bahasa.
(Syarh Muhtasar, hlm. 6-7)
Istilah yang menggambarkan metode Îcî adalah tahqiq.
Penyelidikan,
adalah cara untuk mendapatkan kembali secara rasional kebenaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Îcî, para ulama yang hidup pada masanya tidak menyelidiki secara serius pendapat-pendapat yang dianggap benar, sehingga, terutama para ahli kalam, mengalami kesulitan dalam bidang ilmu.
“kīl ü kāl”
telah dibahas, setiap riwayat telah disampaikan tanpa meneliti mengapa hal itu dikatakan dan tanpa menentukan apa yang diwakilinya.
(Jurjani, Syarh al-Mawaqif, I, 22)
Dalam karya-karya Îcî, tahqiq merupakan semacam rekonstruksi, yaitu menelaah kembali suatu pandangan yang dipertahankan, dan sebagai hasilnya mencapai kesimpulan tentang pandangan tersebut, menerimanya dan melanjutkannya atau menolaknya dan menghapusnya dari agenda. Namun, tahqiq harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Kriteria-kriteria ini meliputi menetapkan kebenaran pandangan, mempertimbangkan apa yang diberikannya dan apa yang diambil darinya, serta menentukan tempatnya dalam keseluruhan sistem pemikiran, sehingga mencapai konsistensi dalam pemikiran. Îcî menerima kesesuaian dengan syariat sebagai kriteria kebenaran dalam kalam, penyelesaian masalah akidah yang dihadapi umat Islam pada masa itu sebagai kriteria kegunaan, dan konsistensi logis sebagai kriteria konsistensi.
(al-Mawaqif, hlm. 4-5)
Kritiknya terhadap sikap para ulama pada masanya, yang dianggapnya tidak memadai, juga berakar pada kekurangan yang dilihatnya pada poin-poin tersebut.
Icjî, dalam mendasari keberadaan dan bidang nilai, menganggap data dalam syariat sebagai dasar, dan hanya menganggap akal, dan karenanya logika, sebagai prinsip formal, serta tidak memberinya wewenang di bidang nilai. Dalam sikapnya ini, ia kemungkinan besar mengambil contoh dari Ibn al-Hajib, dan berupaya untuk menyelesaikan proses yang dimulai olehnya, yaitu mereduksi semua bidang ke dalam logika dan pemahaman.
Jawaban 3: Pandangan Teologis
Menurut Îcî
kata-kata
Ilmu ini adalah ilmu yang membuktikan dasar-dasar keyakinan agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad (saw), yaitu membuatnya dapat dipahami dan diterima secara rasional, serta menyingkirkan ide-ide yang bertentangan yang muncul atau mungkin muncul. Objek ilmu ini adalah segala sesuatu yang diketahui, sejauh menyangkut pembuktian keyakinan.
Digunakan saat menentukan subjek
“ma’lum”
konsepnya lebih luas daripada yang ada (mevcûd)
ma’dûmu
juga termasuk di dalamnya. Akibatnya, tidak percaya pada suatu prinsip sama seperti percaya, menjadi bagian dari kajian ilmu kalam, sehingga pemahaman keberadaan yang komprehensif menjadi salah satu unsur penentu ilmu ini. Menurut Îcî, yang mengatakan bahwa ilmu kalam, yang dianggapnya sebagai ilmu terpenting, tidak mendapatkan perhatian yang cukup pada masanya, orang-orang melakukan berbagai pekerjaan untuk kelangsungan tatanan dunia, dan minat setiap orang berbeda-beda dalam ilmu pengetahuan.
Ilmu yang paling penting adalah kalam, yang membahas masalah-masalah seperti keberadaan dan sifat-sifat Sang Pencipta, dan pembuktian kenabian. Khususnya, kenabian, sebagai dasar normatif masyarakat dan landasan syariat, merupakan pokok bahasan utama dalam ilmu kalam.
(al-Mawaqif, hlm. 8; Syarh Muhtasar, hlm. 6)
Menurut posisi yang ditempati oleh Îcî, kalam adalah ilmu yang memungkinkan masyarakat Islam untuk melihat dirinya sebagai sebuah sistem dan menggunakan data eksternal yang dibutuhkannya. Sebagai prasyarat dari kewajiban amali yang dipenuhi oleh masyarakat Islam, keyakinan (akidah) memungkinkan adanya ushul fikih, hadis, dan ilmu-ilmu lainnya, dan ilmu-ilmu ini memastikan kelanjutan masyarakat Islam terwujud di atas dasar-dasar yang benar.
Dalam pemikiran Îcî, akidah dibangun di atas prinsip-prinsip yang tetap. Oleh karena itu, ontologi, dalam arti yang paling umum, membentuk doktrin keberadaan dan merupakan salah satu topik penting dalam ilmu kalam. Keberadaan, sebagaimana dialami manusia, yang terdiri dari proses menjadi dan lenyap, tidak diragukan lagi terjadi dalam suatu keteraturan. Untuk menentukan unsur-unsur tetap dan berubah dari keteraturan ini, selain araz (akibat) dan cevher (substansi), kategori-kategori (makūlāt) juga perlu dibahas sebagai bagian dari masalah keberadaan, sebelum pembahasan ilahiyāt. Penanganan Îcî terhadap masalah araz sebelum cevher (al-Mevâķıf, hlm. 96-181, 182-265) dapat dipahami berdasarkan kenyataan bahwa manusia dapat merasakan hal yang berubah secara inderawi sebelum memahami hal yang tetap secara rasional, dan bahwa hal yang tetap hanya dapat ditentukan melalui studi hal yang berubah. Jika kita memperhatikan masalah keberadaan dengan cermat, kita melihat bahwa masalah ini tidak hanya terdiri dari makhluk yang ada, tetapi juga upaya untuk menempatkan manusia di suatu tempat di antara makhluk-makhluk tersebut.
Oleh karena itu, baik kategori maupun
inti, alam, kehendak, kekuatan, perbuatan, akal
Masalah-masalah seperti itu tidak hanya dibahas sebagai hal yang ada dengan sendirinya (bizâtihî) dan sebagai hasil dari minat intelektual. Hal ini juga terlihat dalam pembahasan teologi, di mana manusia menjadi subjek terpenting, dan upaya dilakukan untuk menentukan posisinya di antara makhluk ciptaan, di satu sisi, dan menentukan statusnya di hadapan Allah, di sisi lain.
Adudüddin el-Îcî mendefinisikan pengetahuan sebagai “sifat yang memberikan kepastian pada subjeknya, tanpa menyisakan kemungkinan sebaliknya”. Menurutnya, titik awal dalam masalah pengetahuan adalah manusia sebagai makhluk yang mengetahui dan kedudukannya di antara makhluk-makhluk lain. Hal ini juga berarti bahwa manusia secara bawaan, tanpa campur tangan atau usaha langsung, memiliki pengetahuan yang mutlak. Hal yang sangat ditekankan oleh Îcî adalah perbedaan dan kesenjangan antara pencipta dan ciptaan dalam segala hal.
(hal. 2)
Dalam berbagai karyanya, hubungan antara pengetahuan, keberadaan, dan nilai memegang tempat yang sangat penting. Îcî menjadikan pengetahuan sebagai subjek agama, berangkat dari premis bahwa pengetahuan harus menjadi dasar bagi ketertiban sosial dan memiliki prinsip-prinsip umum yang dapat dipahami oleh semua orang, dan mengharuskan penelitian berbasis penyelidikan tentang nilai kognitifnya. Nazar, meskipun bukan elemen keyakinan itu sendiri, menjadi prasyarat dari sudut pandang pembuktian keyakinan. Dalam ajaran Îcî, seperti dalam filsafat, penekanannya bukan pada bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, melainkan pada bagaimana pengetahuan dapat digunakan dengan benar dalam proses penalaran untuk mencapai tujuan.
Dalam karya-karya Îcî, pembahasan tentang ilahiyat dan sem’iyat hanya dibahas setelah terbentuknya pandangan terkait masalah keberadaan dan pengetahuan. Topik-topik ilahiyat diletakkan secara rasional, sementara pembahasan sem’iyat ditangani sebagai hubungan Allah-alam dan Allah-manusia sesuai dengan pemahaman manusia. Kerangka konseptual yang disajikan Îcî dalam empat bagian pertama dari karya terkenalnya memungkinkan manusia untuk menawarkan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi di setiap zaman dan tempat. Dalam pemikirannya, iman,
“Membenarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai wahyu.”
yang berarti bahwa hal ini memiliki peran penentu dalam hal tata tertib kehidupan dan moralitas di dunia, terutama karena hubungannya dengan perbuatan baik.
(Cevâhirü’l-kelâm, II/2, hlm. 224-225)
Îcî, yang menyadari perlunya memulihkan stabilitas akibat invasi Mongol pada masanya dan melihat stabilitas ilmiah sebagai sumbernya, memiliki tempat khusus dalam sejarah pemikiran Islam, baik karena menghidupkan kembali tradisi maupun memberikan kesempatan yang sama kepada generasi selanjutnya. Zaman yang dilalui Îcî merupakan masa di mana lebih banyak penataan dan penyusunan kembali tradisi lama untuk dilestarikan daripada pencarian dan pengembangan hal-hal baru.
Masalah terpenting Îcî dan para ulama lain yang hidup di zamannya adalah memastikan bahwa hal-hal yang kebenarannya tidak diragukan lagi dapat dipahami kembali melalui penelitian, dan hal ini disampaikan kepada masyarakat yang hidup dan generasi mendatang. Metode yang diikuti Îcî, khususnya dalam al-Mawâqif selain karya-karya lainnya, ditujukan untuk memecahkan masalah ini.
(bdk. Sarton, III/1, hlm. 629)
Îcî, yang memanfaatkan pemikiran-pemikiran sebelumnya yang tidak membuatnya merasa bergantung ketika berbicara tentang pencapaian tujuan, juga telah menggambar kerangka yang membuat tawaran dan preferensinya bermakna. Karyanya tidak hanya menjadi model bagi generasi mendatang karena sifatnya yang sistematis, tetapi juga karena mencakup sejarah pemikiran.
Iji, karena menggabungkan unsur-unsur rasional dengan sunnah (hadits) baik dalam bidang kalam maupun ushul fikih, tidak memberikan tempat yang independen bagi filsafat dalam pemikirannya. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah, meskipun ia menggunakan unsur-unsur filosofis, ia tidak merasa bergantung padanya, melainkan memilih gaya yang menganggap perlu merujuk pada pendapat orang lain untuk menjelaskan pemikirannya. Hal ini menyelamatkannya dari ketergantungan pada filsafat meskipun memiliki bekal pemikiran filosofis, dan mencegahnya melampaui kerangka kalam. Bahkan, dalam perselisihan dan perbedaan pendapat antara ulama kalam dan filsuf, Iji umumnya berada di pihak ulama kalam, tetapi ia tidak bergantung pada pendapat siapa pun di antara ulama kalam, melainkan mengembangkan pendiriannya sendiri.
Pemikiran Islam dan khususnya pemahaman ilmiah Kesultanan Utsmaniyah
yang meninggalkan kesan abadi
Îcî
Karya-karya ‘nya dibaca sebagai buku teks selama berabad-abad, dan dirinya sendiri juga
Jurjani
dan
Teftazani
bersama-sama membentuk model ulama ideal dari ulama-ulama Ottoman. Sistematis yang dikemukakan Îcî dalam el-Mawâqif, yang menjadi dasar bagi syarah dan catatan kaki dari semua karyanya, telah menjadi contoh, tidak hanya dalam ilmu kalam, tetapi juga dalam ilmu-ilmu lainnya.
(van Ess, Teori Pengetahuan, hlm. 38-39)
Îcî, khususnya terkait dengan esensi bahasa, membahas topik “waz’ (penafsiran) dalam sebuah risalah terpisah dan menjadi pendiri disiplin ini, serta memantapkan konsep “cihet-i vahdet” yang dikembangkan oleh Molla Fenârî dan Mehmed Efendi. Banyaknya risalah tentang waz’iyye dan cihet-i vahdet yang ditulis dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil Îcî dilanjutkan oleh ulama-ulama berikutnya.
Jawaban 4: al-Mawāqīf
Ini adalah karya Adudüddin el-Îcî (meninggal 756/1355) tentang ilmu kalam.
Karya ini ditulis ketika penulis menjabat sebagai qāḍī al-qudāt.
Dinasti Incu
Setelah pendahuluan singkat yang menyatakan bahwa karya tersebut didedikasikan kepada Emir Shiraz pada masa itu, Jalal al-Din Abu Ishaq, karya ini terdiri dari enam bagian. Bagian-bagian yang diberi judul “al-Mawqif” umumnya dibagi menjadi sub-bagian yang disebut “al-Marsad, al-Maqsad”, dan terkadang juga “al-Marsad, al-Fasl, al-Naw’i, al-Qism…”. Bagian pertama al-Mawqif, yang merupakan bagian yang berisi informasi dasar, terdiri dari enam bagian.
Bagian pertama membahas definisi, pokok bahasan, manfaat, kedudukan, dan sebutan ilmu kalam di antara ilmu-ilmu Islam. Bagian kedua membahas definisi ilmu, bagian ketiga membahas jenis-jenis ilmu, bagian keempat membahas pembuktian ilmu yang mutlak, bagian kelima membahas istidlal, jenis-jenis istidlal yang benar dan salah, syarat-syarat, ciri-ciri, dan pentingnya istidlal yang benar dalam mengenal Allah, dan bagian keenam membahas metode-metode untuk mencapai kesimpulan yang diinginkan melalui istidlal yang benar, jenis-jenis dalil dan qiyas.
Bagian kedua karya ini membahas tentang keberadaan dan terdiri dari lima bagian. Bagian pertama, yang membahas masalah keberadaan dan ketiadaan, membahas hubungan keberadaan-materi, tingkatan keberadaan, keberadaan dalam pikiran, dan ketiadaan.
“sesuatu”
Pada bagian pertama, dibahas topik-topik seperti apakah ada atau tidak, keberadaan sebagai ruang eksistensi antara yang ada dan yang tidak ada. Bagian kedua membahas definisi mahiyet, sifatnya yang umum, khusus, sederhana, dan majemuk. Bagian ketiga membahas wujud-kemungkinan-penolakan, kekekalan-kehadapan, dan bagian keempat membahas kesatuan-keragaman serta bagian kelima membahas sebab-akibat, dengan memberikan perhatian pada pandangan berbagai mazhab kalam serta filsuf. Dengan demikian, topik keberadaan dianalisis secara rinci.
Bagian ketiga buku ini, yang membahas tentang araz (atribut), terdiri dari lima bagian. Bagian pertama membahas definisi araz, bagian-bagiannya, pembuktian keberadaannya, serta fakta bahwa araz tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat berpindah tempat dengan sendirinya, tidak dapat memperoleh keberadaan tanpa zat, dan tidak memiliki sifat keberlanjutan. Araz dibahas dalam bagian kedua terkait dengan kategori kuantitas, bagian ketiga dengan kualitas, bagian keempat dengan nisbah (rasio), dan bagian kelima dengan kategori nisbi. Bagian keempat, yang membahas tentang cevher (zat), terdiri dari empat bagian setelah pendahuluan. Bagian pertama membahas definisi zat, pembagiannya menjadi zat majmuk dan zat sederhana, benda-benda di atas bulan dan di bawah bulan, langit, sifat bumi, pencampuran zat majmuk, jiwa dan jenis-jenis jiwa (nabati, hayawani, dan insani), bagian kedua membahas beberapa sifat zat, seperti penciptaan zat dan keterbatasan dimensinya, bagian ketiga membahas jiwa, jiwa natsiqah (akal), hubungan jiwa dengan badan, dan bagian keempat membahas tentang akal.
Dua bagian terakhir dari al-Mawaqif berisi masalah-masalah akidah dari kelam klasik.
Bab kelima, yang membahas topik-topik Ilahiyat, disusun dalam tujuh bagian. Bagian-bagian tersebut membahas secara berurutan tentang keberadaan Allah, sifat-sifat penyucian-Nya, kesatuan Allah, sifat-sifat kesempurnaan-Nya, Rū’yatullah (melihat Allah), perbuatan Allah dan hamba-hamba-Nya, serta Asmaul Husna. Karya ini…
“Sem’iyyât”
Bab terakhir yang berjudul demikian terdiri dari empat bagian.
Nubuwwah (Kenabian)
Bagian pertama, yang membahas topik-topik tersebut, menjelaskan hakikat nabi, mukjizat, kemungkinan rasionalnya pengutusan, pembuktian kenabian Nabi Muhammad, kemuliaan nabi dan malaikat, derajat keutamaan nabi, dan masalah keramat. Bagian kedua
akhirat
bahasan ini membahas kemungkinan adanya akhirat, bahwa hari kiamat akan terjadi bersamaan dengan jiwa dan raga, keadaan surga dan neraka serta orang-orang yang akan masuk ke dalamnya, syafaat, taubat, dan beberapa keadaan akhirat lainnya secara singkat. Bagian ketiga
“Nama-nama dan Hukum-hukum”
di bawah judul
definisi iman dan hubungannya dengan amal,
Kitab ini memberikan informasi tentang kufur dan jenis-jenisnya, murtad besar, dan penjatuhan hukuman kafir. Bagian terakhir kitab ini…
kepemimpinan
Setelah membahas pokok bahasan, dengan judul “Tezyil” (Penutup), disebutkan hadis tentang tujuh puluh tiga kelompok yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, dan dinyatakan bahwa kelompok-kelompok Islam besar dibagi menjadi delapan kelompok, yaitu Mu’tazilah, Syiah, Khawarij, Murji’ah, Naqqariyyah, Jabariyyah, Musyabbihah, dan Najjiyyah. Kemudian, diberikan informasi singkat tentang cabang-cabang kelompok-kelompok ini, dan dinyatakan bahwa kelompok yang selamat (najjiyyah) adalah kelompok Ash’ari dan Salafiyyah. Meskipun jumlah cabang yang disebutkan oleh penulis untuk kelompok-kelompok besar tersebut sekitar enam puluh lima, kemungkinan ia telah memperhitungkan kelompok-kelompok kecil dari beberapa cabang, tetapi tidak menyebutkannya di bawah angka tujuh puluh tiga.
Al-Mawaqif, yang memaparkan pandangan-pandangan teologi Ahl-i Sunnah berdasarkan mazhab Asy’ari, dapat dianggap sebagai teks terpanjang terakhir dalam sejarah kalam klasik.
Sebagaimana diketahui, sejak abad ke-8 (XIV) Masehi, dimulai periode tafsir-tafsir yang komprehensif yang menggabungkan pandangan para ulama terdahulu dan kemudian. Dalam karya ini, selain bentuk-bentuk penalaran dari kitab-kitab kalam klasik yang bermazhab Asy’ari, pengaruh gagasan-gagasan filsafat yang secara tidak langsung dan sebagai reaksi dimasukkan ke dalam isi kalam oleh al-Ghazali sangat terlihat. Kesamaan isi antara al-Mawaqif dengan karya-karya Fakhreddîn ar-Râzî, Syaifuddin al-Amidi, dan Qâdî Bayzâwî menunjukkan bahwa Adududdin al-Iji banyak memanfaatkan karya-karya penulis tersebut. Dalam kitab ini, beberapa judul dan kalimat terlihat diambil langsung dari al-Muhaṣṣal karya Fakhreddîn ar-Râzî.
(al-Muḥaṣṣal, hlm. 18; bandingkan dengan al-Mawāqif, hlm. 14)
Berbagai studi telah dilakukan pada al-Mawaqif, dimulai dari murid-murid Adud al-Din al-Iji. Karya Syekh Syarif al-Jurjani, yang diselesaikan di Samarkand pada tahun 807 (1404) dengan judul Syarh al-Mawaqif, adalah yang paling terkenal di antara syarah-syarah al-Mawaqif. Sumber-sumber menyebutkan bahwa kitab ini juga telah disyarah oleh Syams al-Din al-Kirmani, Sayf al-Din al-Abhari, sebagian oleh Ala al-Din Ali al-Tusi (Kashf al-Zunun, II, 1891), dan Haydar al-Harawi. Disebutkan bahwa Ibnu al-Naqib al-Halabi menulis syarah untuk bagian al-Mawaqif yang berkaitan dengan astronomi. Kılıçzade İshak Çelebi memiliki sebuah karya berbahasa Arab berjudul Risale-i İmtiĥâniyye, yang ditulisnya untuk ujian menjadi mudarris di Sahn-ı Seman, berdasarkan sebuah topik yang diberikan kepadanya dari al-Mawaqif dan diserahkan kepada dewan ujian.
(Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, no. 810; lihat juga Erdem, sy. 91 [1994], hlm. 112-113)
Jawaban 5: Karya-karya lainnya
Cintaku padamu.
Mempertimbangkan bahwa karya ini ditulis sebelum al-Mawāqif, tampaknya lebih tepat untuk menganggapnya sebagai bentuk awalnya (bukan ringkasannya) (Keşfü’ž-žunûn, II, 1892). Terdapat berbagai salinan dan telah diterbitkan oleh Abu’l-Ala al-Afifi.
al-Aqāid al-Aḍudiyyah.
Karya ini diselesaikan dua belas hari sebelum kematian Îcî dan ditulis untuk dihafal di madrasah, merupakan risalah ringkas yang berisi pokok-pokok akidah yang telah disepakati. Karya ini telah dikomentari oleh banyak ulama. (Keşfü’ž-žunûn, II, 1144-1145)
Risalah (al-Maqālah al-Muqarrarah) dalam Meneliti Kalam Nafsi (Risalah tentang Kalam Allah).
Beberapa salinan dari karya yang diberi catatan kaki oleh Kemalpaşazâde dapat ditemukan di perpustakaan-perpustakaan di Istanbul.
Syarh Muhtasari al-Muntahe.
Ini adalah sebuah syarah yang ditulis oleh Ibnu’l-Hajib sendiri atas kitab al-Muħtaśar, yang merupakan ringkasan dari kitab Müntehe’s-sûl wa’l-emel karya Ibnu’l-Hajib.
Adab al-Bâhs, al-Adab al-Adudiyyah, ar-Risalah al-Adudiyyah.
Dalam risalah yang terdiri dari “sepuluh baris” yang membahas jalan dan metode penalaran serta berisi aturan-aturan ilmu nazar, penulis menerapkan metode penalaran yang dia kemukakan dalam berbagai karyanya (misalnya, lihat Şerĥu Muħtaśar, hlm. 8, 9).
Karya yang telah diajarkan dan dihafal di madrasah selama berabad-abad.
(Istanbul 1267, 1274; Kairo 1306, 1310)
banyak catatan kaki dan komentar telah ditulis di atasnya.
(Taşköprizade, hlm. 972; Keşfü’ž-žunûn, I, 41)
Hasyiyatul-Kasyyaf.
Karya ini, yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab tabakat, merupakan catatan kaki pada kitab al-Kashshaf karya al-Zamakhshari, dan salinannya terdapat di Perpustakaan Süleymaniye.
(Beşir Ağa, no. 1113; untuk dua contoh yang diambil dari salinan ini, lihat Yılmaz, hlm. 45-47)
Penelitian Tafsir dalam Pengaruh Penerangan.
Karakteristik karya ini, yang merupakan tafsir mandiri, adalah pendekatan penulis yang membahas ayat-ayat dalam kesatuan makna. Karya ini didasarkan pada ilmu bahasa dan filsafat bahasa, namun juga menyentuh masalah-masalah yang berkaitan dengan ushul fikih dan kalam, serta topik-topik filosofis. Dalam penafsiran ayat-ayat hukum, karya ini umumnya mengikuti mazhab Syafi’i, tetapi juga menyebutkan pandangan mazhab-mazhab lain.
Kutipan-kutipan dalam karya tersebut yang menyebutkan el-Keşşâf, Mefâtîĥu’l-ġayb, Lübâbü’t-tefsîr, dan lebih sering lagi, Anwâr ut-Tanzîl karya Qāḍī Bayḍāwī, telah membuat beberapa peneliti yakin bahwa ini mungkin merupakan sebuah syarah yang ditulis untuk tafsir Bayḍāwī.
(İA, V/2, hlm. 922; EIr., III, 270)
Ahlak-ı Adudiyye.
Putra Taşköprü,
ilmu politik
Ia mencatat bahwa ia menuliskan sebuah syarah (komentar) pada risalah ini di masa mudanya, yang ia sebutkan sebagai karya terpenting yang ditulis tentang topik tersebut. (Miftâĥu’s-saâde, hlm. 489)
al-Fawaid al-Ghiyasiyyah.
Karya ini merupakan ringkasan dari bagian-bagian tentang ma’ani, bayan, dan badi’ dari kitab Miftâhu’l-ulûm karya Sekkâkî, dan didedikasikan kepada Gıyâseddin Muhammed, menteri Olcaytu Khan.
Al-Madhal fi ‘Ilm al-Ma’ani wa al-Bayan wa al-Badi’.
Karya ini, yang ditulis sebagai ringkasan dari Telħîśü’l-Miftâĥ karya Hatîb el-Kazvînî, dilengkapi dengan sebuah bagian tentang hubungan-hubungan persamaan di bagian akhirnya.
ar-Risâlatu’l-Ważiyyah (Risalah tentang Wajib).
Ini adalah risalah setebal satu setengah lembar. Risalah yang bertujuan untuk membangun hubungan antara bahasa dan keberadaan berdasarkan prinsip logika ini, pada bagian pertama melakukan pembagian logis, pada bagian kedua menunjukkan perlunya membangun hubungan antara klasifikasi dengan makhluk yang ada, dan pada bagian ketiga, hubungan ini diikat dengan suatu prinsip.
Dalam risalah ini, dilakukan upaya untuk mendasarkan bahasa pada prinsip-prinsip logika, seperti yang telah dicoba oleh para positivis logis pada masa modern, khususnya Rudolf Carnap.
Salam dan doa…
Islam dengan Pertanyaan-Pertanyaan